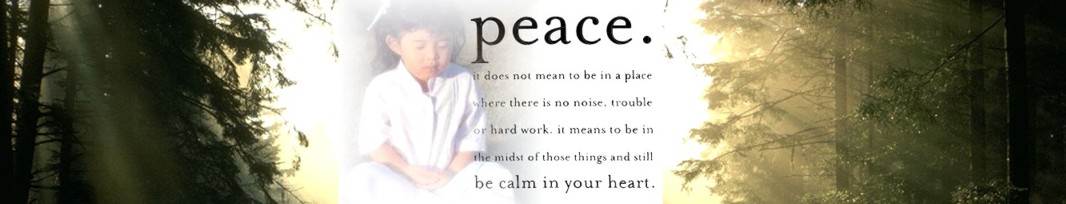Bukan tentang pendalaman materi dalam buku USING NO WAY AS WAY! yang ingin saya ungkapkan kembali disini, tapi hanya menunjukkan bahwa buku saya hanyalah sebab sekaligus akibat dari lingkungan dari zaman tempat saya belajar. Banyak hal yang terlibat dan saya berusaha untuk menyajikan kerangka berpikir dari apa yang pernah saya alami itu.
Ada delapan buah pokok pemikiran yang mempengaruhi USING NO WAY AS WAY!
1. ETIKA
2. AFIRMASI
3. KEBAHAGIAAN
4. PENDEKATAN MISTIK
5. PLURALISME
6. PRAKTIK MEDITASI
7. KESUKSESAN
8. WAWASAN EKOLOGIS
ETIKA
Pelajaran Etika yang tidak disuguhkan dalam bentuk perintah kitab suci saya dapatkan dari Buddhisme dan Nietzsche. Perkembangan Buddhisme banyak diwarnai bentuk formal yang terasa ekslusif –sebagaimana agama-agama lain pada umumnya, namun saya lebih suka bukan pada ritualitas yang mungkin nyaman bagi orang tertentu. Secara umum, semua agama memiliki bentuk kenyamanan sesaat (dalam bentul ritual atau keimanan yang kaku –bahkan yang terakhir ini sering menjadi sumber konflik sosial yang berkepanjangan) yang jauh dari fungsi spiritual. Freud pernah mengkritik agama sebagai bentuk kepanjangan masa kanak-kanak yang rindu dengan orang tua dan menganggap Tuhan, Dewa, atau bentuk sakral tertentu sebagai bentuk pengharapan. Etika tidak harus dimaknai sebagai keterpaksanaan, tapi pada upaya melatih kesadaran diri.
Nietzsche memperkenalkan etika majikan, sebagai pembanding etika budak. Etika budak adalah melakukan sesuatu berdasarkan ketakutan. Bagaimana mungkin orang takut akan menjadi lebih baik? Saya pernah melakukan refleksi dengan bertanya seperti itu. Untuk itu butuh etika majikan, yang bukan karena ‘desakan’, tapi karena kesadaran diri. Nietzche membahas dengan aforisma yang mungkin terlihat terlalu kritis sehingga etika Nietzsche dianggap atheisme yang tak berspiritual.
Buddha adalah sosok yang begitu manusiawi yang berusaha memecahkan permasalahan hidup manusia, yaitu penderitaan. Polemik tentang klaim kebenaran akan menjadi mandul dan tak berarti, karena kita yang merasa “benar” ternyata masih menderita dan tidak bisa menumbuhkan cinta kasih. Bukankah kebahagiaan itu adalah cinta kasih?
Pemahaman tentang etika akan semakin jelas, ketika etika bukan dimengerti sebagai perintah yang memberi pilihan ‘neraka’ atau ‘’surga’, namun dengan dilandasi kebijaksanaan, tidak lain buah pemahaman hidup.
Kebijaksanaan akan membuahkan kebahagiaan dan cinta kisah. Tidak pernah ketakutan mampu menghasilkan cinta kasih dan kebahagiaan. Dan orang yang bahagia selalu memiliki etika yang lebih baik.
AFIRMASI
Istilah “Afirmasi” saya dapatkan dari ulasan tentang pemikiran Nietzsche. Saya lanjutkan tentang pengertian kebijaksanaan yang saya singgung sebelumnya.
Kebijaksanaan adalah pemahaman intuisi yang mempersiapkan kita untuk berani menghadapi ketidakpastian dalam hidup.
Kemampuan menghadapi hidup ini adalah konsep afirmasi Nietzsche, yang sering diungkapkan dengan kalimat “berkata ‘ya’ pada kehidupan”.
Pandangan Buddha tentang kebijaksanan adalah kemampuan memahami ketidakpuasan sebagai kewajaran, pengakuan adanya perubahan yang silih berganti, dan juga kepalsuan ego yang merupakan ilusi terhebat yang pernah dimiliki manusia.
Afirmasi ini paling sering salah dipahami banyak orang sebagai bentuk materialisme yang hanya mengakui dunia fana ini saja. Secara ekstrim, dituduh sebagai anti agama yang menolak keberadaan surga maupun neraka.
Saya memahami bahwa pengakuan akan kefanaan hidup bukan untuk membuat kita melarikan diri dari kefanaan itu --dengan menggantinya dengan fantasi “kesenangan”. Jika kita terus melarikan diri dari kenyataan, maka kita selalu tidak siap menghadapi masalah. Bagaimana mungkin kebahagiaan bisa tumbuh jika kita selalu menghindari dari masalah?
KEBAHAGIAAN
Ini adalah bagian yang paling sering salah dipahami. Sering ada upaya promosi bahwa seseorang setelah mengikuti agama tertentu menjadi sukses, mendapat pahala Tuhan atau Dewa, dan hidup berkelimpahan dan bahagia.
Padahal konsep kebahagiaan yang dipromosikan itu bukanlah kebahagiaan sejati, itu hanya kesenangan yang dianggap kebahagiaan. Kadang saya pikir, agama mulai menggunakan cara-cara yang jauh dari spiritualitas yang telah disungguhkan para nabi atau pendiri agama itu sebelumnya.
Kesenangan dan kebahagiaan adalah berbeda.
Kesenangan selalu eksternal dan memiliki syarat-syarat tertentu. Kesenangan itu hanyalah sisi lain dari penderitaan. Jika kondisi atau syarat-syarat itu lenyap, maka apa yang disebut kesenangan segera menjelma menjadi penderitaan.
Kesenangan ini jika kita perhatikan lagi, selalu berada dalam konsep “hak milik”.
Jika orang cantik itu menjadi milik, maka senang. Jika gagal dimiliki, maka menderita. Jika yang cantik itu berubah menjadi buruk rupa, itu juga menderita.
Kebahagiaan adalah internal, tidak tergantung dengan syarat-syarat tertentu.
Kebahagiaan sejati itu tanpa sebab, karena itu kebahagiaan itu tanpa akhir. Sesuatu yang memiliki sebab akan berakhir. Ajahn Sumedho pernah berujar, “Jika ingin menderita, carilah sesuatu yang memiliki awal”.
Kebahagiaan sejati melampaui pahala, musibah, berkah, keberhasilan, baik, buruk, dll. Kebahagiaan ini menjadi tujuan dari semua tradisi spiritual. Yang dipahami sebagai yang tanpa sebab dan tanpa akhir --inilah yang disebut keabadian.
Penghalang ‘keabadian’ ini adalah diri sendiri, maka pemecahan masalah juga harus melalui diri sendiri. Sebab penderitaan adalah masalah universal [murni karena diri sendiri dan tidak ada hubungannya dengan ras, suku maupun agama], maka solusinya tentu juga harus universal.
PENDEKATAN MISTIK
Pendekatan mistik, bukanlah hal-hal gaib, supranatural, dll. Pendekatan mistik yang saya maksud mengacu pada mistisisme, yang sering disebut sbeagai harta karun terpendam abad ke-20. Banyak buku yang menjadi rujukan saya tentang mistisisme, yang membuka perspektif spiritualitas yang sudah ada pada agama-agama yang sudah ada.
Beberapa orang menyebutkan bahwa mistisisme merupakan reaksi atas semakin menurunnya fungsi organized religion yang ada saat ini. Kegiatan beragama kadang memperkuat sumber konflik terutama jika yang dipahami hanya aspek formal dan lahiriahnya saja. Secara ezensi, saya mengacu pada pandangan William James bahwa agama mestinya menjadi rumah bagi ‘agama personal’.
Tokoh-tokoh agama yang open minded berupaya kembali pada jatidiri spiritual pada agamanya. Aktivitas religi seperti inilah yang dibutuhkan dan justru memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Sufisme, Buddhisme, Christian Mistisism, Taosime, dll, membawa kesimpulan yang sama, bahwa pemahaman tertinggi haruslah dialami. Kaum Sufi sering menyebutkan bahwa upaya pencarian Tuhan adalah salah, karena itu berarti mengingkari adanya Tuhan pada saat ini. Tuhan bukan dicari, tapi disadari –karena Tuhan telah ada sekarang.
Penganut Christian Greek (Kristen Yunani) memahami iman dengan cara yang berbeda sebagaimana otoritas iman yang kita kenal pada umumnya. Iman (faith) mestinya harus dialami, menjadi pengalaman. Jika iman baru menjadi dogma, itu artinya perjalanan spiritualitas belumlah selesai, karena pengalaman akan ‘Tuhan’ mesti dialami.
Ada ungkapan-ungkapan pengalaman seperti ini.
Santo Benedict menyebutkan, “Jika Anda pikir itu Tuhan, maka itu bukan Tuhan”. Kalimat mirip dengan ungkapan Zen yang terkenal, “Jika ketemu Buddha, bunuh Buddha itu”.
Pendekatan mistik itu yang membuat saya memilih USING NO WAY AS WAY sebagai judul. Yang mengingatkan bahwa jika ingin bahagia, maka konsep tentang kebahagiaan itu juga harus di lenyapkan.
Perjalanan mistik pada akhirnya, membuat Tuhan atau realitas yang tertinggi tidak bisa dikatakan. Orang Jawa kuno menyebutkan “tan keno kinoyo ngopo” –tidak dapat di apa siapakan. Lalu, Lao Tze menggaris bawahi dalam sebuah sikap diam, “Orang yang tahu akan tidak bicara” –walaupun belum tentu orang diam adalah pertanda mengerti.
Diam adalah hening, bukan pertanda tidak tahu. Diam adalah tahu dan merasakan, mengada bersama Tuhan, larut dalam keabadian –suatu kemenjadian yang membahagiakan dan memberi kedamaian. Paulus memberikan perspektif Ketuhanan dalam praktik dalam ungkapan, “Allah itu kasih”.
Yang paling menarik, adalah ketika pendekatan mistik ini dipelajari, dengan membuka-buka kitab suci, kita akan menemukan kerangka-kerangka pemahaman baru yang belum pernah kita jamah sebelumnya.
Ternyata kitab suci tidak boleh dipahami secara hurufiah. Ini semacam cerita rakyat atau dongeng atau legenda, yang harus dipahami dari kedalaman makna –bukan secara hurufiah.
PLURALISME
Pluralisme bukanlah sinkretis, konsep “gado-gado”, atau sekedar ajang silaturahmi –semacam basa-basi tokoh agama.
Pluralisme adalah pengakuan akan keragaman dan penghargaan atas perbedaan berpikir, yang bermuara sebuah tujuan yaitu kerjasama untuk mengatasi permasalahan bersama, seperti ketidakpedulian, kekerasan sosial, materialisme, dan krisis kemanusiaan.
F.X.E.Armada Riyanto, CM., dalam Dialog Agama dalam Pandangan Gereja Katolik, (Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 1995), hal 45-46, menyebutkan:
“Sebuah wajah gereja yang inklusif tercantum dalam Gaudium Et Spes 22 dikatakan bahwa upaya keselamatan diluar intansi gereja adalah mungkin, karena pekerjaan Roh Kudus tidak dibatasi oleh Gereja.”
Kutipan diatas adalah salah satu pemahaman agama inklusif. Penekanan ajaran agama yang inklusif juga ada agama-agama lainnya. Paling tidak inklusivitas telah menjadi bagian dari praktik keagamaan walaupun secara grass root masih banyak diwarnai identitas agama yang tidak memberi tempat pada rasa empati, kesalingpengertian, dan penghargaan terhadap mereka yang berbeda agama/pandangan hidup.
Tujuan kerjasama lintas agama juga bisa dalam hal untuk saling menginspirasi dan memperkaya pengalaman spiritual masing-masing.
Dalai Lama sering berujar kepada orang yang berbeda agama seperti ini.
“Akan lebih baik, jika Anda mencari dalam tradisi Anda masing-masing”
Pluralisme akan semakin fasih jika setiap orang lebih menitik beratkan ezensi daripada aspek lahiriah agama saja.
PRAKTIK MEDITASI
Spiritual Quotient (SQ) adalah penjelasan psikologi tentang spiritualitas setelah dunia dikejutkan dengan konsep Emotional Intelegence.
Saya berpendapat bahwa SQ tidak lengkap dipahami sekedar teori sebagai bahan pembelajaran intelektual. SQ mesti memiliki rujukan dalam hal displin praktik, suatu jenis terapi mandiri yang membantu menumbuhkan SQ.
Disiplin praktik tersebut adalah meditasi.
Apa yang terjadi dalam praktik meditasi?
Penjelasan sederhananya adalah seperti ini.
Spiritualitas adalah kemampuan menghadapi ketidakpastian dalam hidup. Kemampuan ini akan menumbuhkan kebahagiaan dari dalam. Jika kebahagiaan bukanlah ekternal –sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, berarti metode yang digunakan justru dengan berlatih “melepas”, bukan “mendapatkan”.
Praktik meditasi adalah berlatih “melepas” pada tingkat mikro.
Mikro disini mengacu pada obyek meditasi yang sederhana, seperti sensasi napas, sensasi tubuh, dll.
Walaupun mikro, tapi praktik ini memberikan hasil yang baik pada tingkat makro.
Tingkat mikro ini memungkinkan praktisi masuk pada level kesadaran yang lebih dalam. Dalam dunia psikologi , tingkat pikiran itu disebut bawah sadar.
Ketidakbahagiaan kita telah merasuk pada level bawah sadar, karena itu butuh pemahaman intuisi pada level kesadaran yang sama. Kebiasaan yang dilatih dalam level bawah sadar akan memberikan pengaruh ketika pikiran berada dalam keadaan sadar pada kehidupan sehari-hari.
Praktik Meditasi ini adalah Spiritual-Hypnosis.
Inspirasi terbesar dari praktik meditasi adalah retret meditasi yang pernah saya ikuti, terutama vipassana dan Zen. Banyak pararelisme dari guru-guru meditasi yang pernah ada seperti Ajahn Chah, Thich Nhat Han, Cheng Yen, Guo Jun Fashi, Sogyal Rinpoche, Goenka, Sayadaw U Pandita, dll.
KESUKSESAN
Kesuksesan tidak selalu bersifat materi, seperti memiliki penghasilan yang besar, memiliki rumah mewah, mobil mewah, dll. Saya lebih mengacu pada pandangan Stephen R. Covey yang lebih tertarik menyebutkan efektivitas dari pada kesuksesan. Efektivitas disini berkaitan dengan pertumbuhan pribadi yang melibatkan kehidupan sosial dalam organisasi yang dilakoninya, yang mengarah pada tercapainya visi dan misi.
Visi dan misi pribadi mesti didasari kebahagiaan. Apa yang kita lakukan adalah mencerminkan siapa diri kita. Demikian juga misi dan visi. Saya rasa problematik kehidupan berawal dari kekeliruan dalam menentukan misi dan visi.
Jika kita menentukan visi dan misi berupa kesenangan-kesenangan sesaat, maka dengan mudahnya kita akan meninggalkan upaya-upaya mengarah pada visi dan misi tersebut. Atau seandainya kita berhasil meraih kesenangan itu, hidup kita tetaphampa dan tetap tidak tahu cara bahagia. Tapi jika kita memiliki visi dan misi yang memiliki nilai dan layak diperjuangkan, maka kita akan terus pada jalur upaya itu. Menariknya, visi dan misi sejati selalu memberi kebahagiaan baik selama proses maupun setelah berhasil diraih, akan selalu ada kebaikan dan kebahagiaan.
Pada umumnya orang berpikir bahwa harus sukses dulu baru bahagia.
Dalam pemahaman spiritual, justru sebaliknya. Bahagia dulu baru sukses!
Dibutuhkan proaktivitas spiritual, yaitu: berbahagia saat ini.
Dan hal itu dilatih dalam praktik meditasi.
WAWASAN EKOLOGIS
Wawasan ekologis adalah salah satu ciri-ciri spiritualitas. Seperti yang diungkapkan Lao Tzu, “Ketika ada kedamaian dalam diri, maka ada kedamaian di dunia”. Ada pengaruh antara keberhasilan diri dengan keberhasilan sosial secara umum. Teori-teori Fisika kontemporer seperti teori Chaos telah membuktikan hal itu.
Pandangan Fritjof Capra telah menginpirasi saya untuk memahami spiritualitas dalam konteks wawasan ekologis. Karena jika tidak, maka tidak ada bedanya dengan praktik yang eksklusif, yang tidak bisa digunakan dalam kehidupan bermasyarakat.
Apapun pemahaman tentang hidup, ideologi, agama, sistem filsafat, apapun, perlu dieksekusi pada level individu.
Dan apa yang kita lakukan (eksekusi), itu akan berpengaruh secara sosial.
* * *
Delapan buah pokok pemikiran -- (1) ETIKA, (2) AFIRMASI, (3) KEBAHAGIAAN, (4) PENDEKATAN MISTIK, (5) PLURALISME, (6) PRAKTIK MEDITASI, (7) KESUKSESAN, (8) WAWASAN EKOLOGIS – walaupun terkesan ‘berat’, tapi saya mencoba menyajikannya dalam bentuk sederhana, gaya penyampaian how to, dalam USING NO WAY AS WAY!
USING NO WAY AS WAY meramu filsafat, psikologi, meditasi, dan spiritualitas dalam sebuah benang merah, yang berpuncak pada pedoman praktis. Metode menuju kebahagiaan sejati adalah USING NO WAY AS WAY (ketanpatujuan sebagai bagian dari praktik).
Semoga buku yang saya tulis itu menginspirasi dan memberikan paradigma baru sehingga membantu kita memiliki sikap yang lebih membahagiakan.
Be Happy!