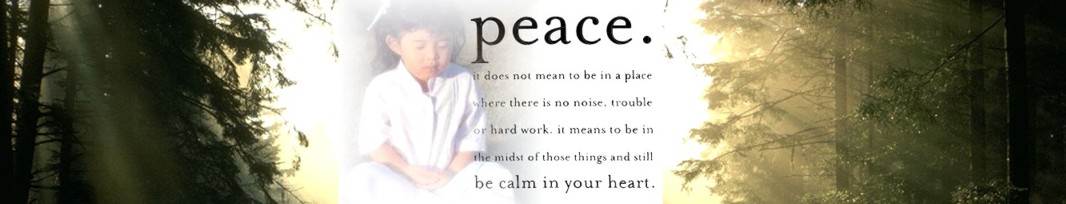"Setiap bentuk penderitaan muncul dari usaha."
(Sang Buddha)
Sering saya sendiri ketika membaca sesuatu lalu sejenak mengguman sambil meninjau ulang apa yang barusan saya pelajari, saya menjadi merasa mengerti. Tanpa saya sadari hal itu selalu melibatkan sebuah asumsi. Jika dirangkai dalam sebuah kalimat, asumsi itu kurang lebih seperti ini: "Aku lebih tahu dibanding yang lain."
Ketika mendengar pendapat orang lain yang masih satu atribut dengan saya, entah atribut agama, kelompok, atau bentuk persamaan lain, saya selalu berkata dalam hati.
"Ah, kamu hanya tahu sedikit, sementara aku tahu hingga logika yang paling dalam."
Lalu, saya menceritakan hal-hal baru yang kupelajari itu.
Orang itu terkagum-kagum, dan membenarkan apa yang saya ungkapkan.
Namun ketika saya mengungkapkan hal itu pada orang yang beda atribut. Yang terjadi hanya perbedaan, dan saya terancam oleh cara berpikirnya itu.
Padahal saya tidak mungkin berkuasa untuk mengatur jalan pikiran orang lain.
Dengan sekedar mengurangi penderitaan dalam pikiran, saya mencoba merelakan. Biarkan setiap orang menganut jalan pikirannya sendiri.
Bukan hanya itu, saya mencoba menyelami apa yang dipahaminya.
Ternyata setiap pandangan muncul dari pengalaman-pengalaman pribadi yang begitu unik. Ibarat yang diungkapkan Heraklitos: "orang [yang sama] tidak akan menginjak air sungai yang sama untuk kedua kalinya." Apalagi orang yang berbeda? Mengapa setiap orang harus dipaksakan dalam sebuah ide?
Semakin kita tidak sibuk dengan asumsi, kita bisa melihat di depan kaca lebih jeli.
Mengapa kita terobsesi oleh persamaan? Apa yang sama? Sebuah bentuk yang disebut "sama" selalu terdiri oleh kombinasi titik-titik yang berbeda. Sama itu tidak ada!
Jika memang ada persamaan, itu hanya asumsi.
Sungguh aneh. Kita suka berasumsi tentang persamaan, tapi kita juga berasumsi tentang perbedaan.
Persamaan menjadi tujuan yang menggerakkan nafsu.
Namun ketika "persamaan" itu mendekat, kitapun terancam dengan "persamaan" itu. Jika semua orang sama pintarnya dengan diriku, lalu bagaimana dengan aku?
Kita selalu repot dengan usaha mengatur dunia, yang tidak terjangkau dengan kekuasaan kita.
Kapan kita akan berhenti?
Selasa, 23 Desember 2008
Rabu, 10 Desember 2008
BERMEDITASI DI KALA SAKIT
“Apa yang telah saya pelajari adalah rasa lelah yang dibawa oleh
rasa sakit itu tumbuh karena kita melawannya.
Hal yang harus dipelajari adalah bagaimana kita dapat menyatu
dengan rasa sakit tersebut...”
(Tenzin Palmo)
Dengan teknik yang benar, meditasi akan mengistirahatkan pikiran sehingga akan mempercepat proses penyembuhan di kala sedang sakit.
Apa yang harus dilakukan ketika tubuh sakit?
Apakah menyesal? Marah? Benci dengan keadaan tubuh yang tidak produktif?
Atau malah sibuk berpikir urusan kantor? Kerjaan yang menumpuk?
Semua itu tidak ada gunanya.
Meditasi di kala sakit yang bisa kita praktekkan adalah melepas semua beban pikiran dengan cara menerima kondisi tubuh yang sakit itu.
Jika ada sensasi pegal, pusing, tegang, terima dan alami rasa tegang itu.
Jangan mengontrol atau berusaha mengendalikannya.
Tugas kita bukan mengendalikan, tapi hanya mengalami apa yang terjadi.
Sakit hanya sekedar sakit, tidak akan bisa lebih dari itu.
Guru Tozan Ryokai suatu saat ditanya oleh seorang bhiksu,
"Pada saat dingin atau panas datang dalam meditasi, bagaimana kita menghindarinya?"
Guru menjawab, "Mengapa kamu tidak beralih pada tempat tidak ada panas atau dingin?"
Bhiksu itu bertanya, "Apakah tempat yang tidak panas maupun dingin?"
Guru menjawab, "Pada saat terasa dingin, guruku, [menyarankan] buat dirimu terus dalam dingin; pada saat terasa panas, guruku [menyarankan], buat dirimu terus dalam panas."
Pada saat tubuh sakit, jangan berpikir sehat. Terima saja sakit itu!
Pikiran yang dualisme adalah penyebab ketegangan, dan hal itu justru membuat proses penyembuhan semakin lambat.
Mungkin aneh ketika sakit tidak berharap untuk sehat. Tapi memang itulah jalan keluarnya –menyatu dengan rasa sakit.
rasa sakit itu tumbuh karena kita melawannya.
Hal yang harus dipelajari adalah bagaimana kita dapat menyatu
dengan rasa sakit tersebut...”
(Tenzin Palmo)
Dengan teknik yang benar, meditasi akan mengistirahatkan pikiran sehingga akan mempercepat proses penyembuhan di kala sedang sakit.
Apa yang harus dilakukan ketika tubuh sakit?
Apakah menyesal? Marah? Benci dengan keadaan tubuh yang tidak produktif?
Atau malah sibuk berpikir urusan kantor? Kerjaan yang menumpuk?
Semua itu tidak ada gunanya.
Meditasi di kala sakit yang bisa kita praktekkan adalah melepas semua beban pikiran dengan cara menerima kondisi tubuh yang sakit itu.
Jika ada sensasi pegal, pusing, tegang, terima dan alami rasa tegang itu.
Jangan mengontrol atau berusaha mengendalikannya.
Tugas kita bukan mengendalikan, tapi hanya mengalami apa yang terjadi.
Sakit hanya sekedar sakit, tidak akan bisa lebih dari itu.
Guru Tozan Ryokai suatu saat ditanya oleh seorang bhiksu,
"Pada saat dingin atau panas datang dalam meditasi, bagaimana kita menghindarinya?"
Guru menjawab, "Mengapa kamu tidak beralih pada tempat tidak ada panas atau dingin?"
Bhiksu itu bertanya, "Apakah tempat yang tidak panas maupun dingin?"
Guru menjawab, "Pada saat terasa dingin, guruku, [menyarankan] buat dirimu terus dalam dingin; pada saat terasa panas, guruku [menyarankan], buat dirimu terus dalam panas."
Pada saat tubuh sakit, jangan berpikir sehat. Terima saja sakit itu!
Pikiran yang dualisme adalah penyebab ketegangan, dan hal itu justru membuat proses penyembuhan semakin lambat.
Mungkin aneh ketika sakit tidak berharap untuk sehat. Tapi memang itulah jalan keluarnya –menyatu dengan rasa sakit.
JANGAN TAKUT!
Diriku mungkin mirip seperti tokoh Faust yang ditulis oleh Goethe, pujangga Jerman yang tersohor itu. Hanya saja aku bukan menjual diri ke setan. Lebih tepatnya, setan dalam kisah Faust itu, saya mengerti, bukan sebagai mahkluk yang berada di luar, yang selalu menjebak manusia untuk jatuh dalam dosa. Setan itu adalah simbol dari kemerosotan yang masih berada dalam diri pikiran kita sendiri.
Kita tidak perlu kekanak-kanakan. Jika memang ada yang berhasil menjebak saya, itu karena saya telah memberinya peluang untuk menjebak diriku. Pada akhirnya, akulah yang menjadi penyebab atas apa yang aku alami ini.
Banyak belajar adalah aksi yang didasari obsesi akan kepastian. Kepastian akan keberhasilan. Sejak kecil kita didoktrin untuk sekolah biar pintar, dan buntutnya selalu hidup sukses dan memiliki kekayaan berlimpah. Orang tua sering menasihatkan anak sulungnya untuk sukses lebih dulu, lalu ikut mengangkat harkat dan martabat adik-adiknya. Cita-cita yang tidak buruk, tapi sebenarnya bukan itu yang perlu menjadi tujuan kita.
Faust dikisahkan sebagai orang pintar yang gila ilmu, yang ingin belajar apa saja. Hingga suatu saat ingin lebih hebat lagi, dia menjual diri ke setan dan konon setan itu akan berjanji memberikan segala yang dimauinya.
Beberapa sastrawan mengartikan Faust sebagai simbol arogansi Barat, yang dirasa telah mencapai puncak peradaban. Kita tahu semua ilmu, ideologi, gaya hidup, bahkan lagu selalu berkiblat pada Barat. Jika tidak bisa mengikuti trend Barat, kita dianggap terbelakang dan ketinggalan zaman. Tapi aku mengartikan Faust sebagai diriku, sebagai diri kita semua, yang terobsesi mengejar segala kepastian dalam hidup.
Suatu saat aku terkejut. Bukankah Nietzsche, Sartre, Freud, mereka semua adalah orang pandai yang banyak ilmu, tapi mereka adalah orang yang menderita? Bukankah diriku juga, walaupun aku tidak sejenius mereka, tapi banyak buku yang kupelajari, aku jadi terluka oleh perasaan “sok tahu” yang membanggakan ini.
Benarkah banyak tahu itu otomatis tidak membuat kita bahagia? Apa tujuan hidup? Mungkin untuk lebih dekat dengan Tuhan. Atau mungkin untuk melayani Tuhan. Tapi sering aku jumpai mereka yang mengaku sebagai “pelayan Tuhan” justru tidak bisa melayani sesamanya dengan lebih baik. Mungkin dipikirnya orang lain bukanlah Tuhan, karena itu tidak dilayani sebaik Tuhannya.
Aku tidak suka dengan ide-ide Tuhan. Bukan berarti aku tidak berTuhan? Tapi karena Tuhan mudah sekali dipelintir demi hasrat pemenuhan pribadi, seperti opini pribadi, prinsip diri, termasuk identitas kelompok. Tuhan sebagai sosok yang agung, justru menjadi sosok yang paling mudah dikibuli manusia. Tuhan menjadi sebuah kemandekan, semacam kepastian yang dipaksa-paksakan.
Filsafat India yang menemukan angka nol, tidak menyukai kepastian mutlak. Bahkan Nagarjuna menyebutkan segalanya sebagai kosong, sunya. Kosong bukanlah atheis, tapi justru pemahaman akan realitas yang paling utuh dan sempurna. Kosong membuat kemandekan tidak memiliki ruang. Bahkan istilah “Tuhan” itu gak perlu lagi. Jika memang ada “Tuhan”, maka yang paling baik adalah tidak mendefinisikannya. Jika terpaksa, gunakan istilah yang berkonotasi bukan kemandekan. Entah itu Sunya, Tao, Tuhan Mistik, atau sekedar simbol. Theis tidaklah lebih bagus dibanding Atheis. Itu hanya istilah yang menjebak. Lebih penting menjadi spiritualis daripada Theis ataupun Atheis.
Spiritualitas adalah pengalaman yang diiringi penghayatan yang seutuhnya, saking utuhnya dia tak lagi berkata-kata. Berkomat-kamit adalah pertanda tidak tahu. Semakin banyak berbicara, dia semakin tidak bisa menjadi utuh. Robert Bernadette yang terinspirasi dengan Mistik Kristen menyebutkan hilangnya diri adalah memahami Tuhan. Selama ada diri yang berpikir, maka Tuhan itu tidak dapat diketahui. Konsekuensi, ketika Tuhan itu menjadi pengalaman, maka “tak terkata” adalah hasilnya.
Saya teringat sebuah kalimat bijak.
“Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan.” Itu ujar Sri Pannavaro Mahathera.
Aku tak mengerti arti ucapan itu pada waktu pertama kali mendengarnya.
“Ah, itu hanya permainan kata-kata,” demikian pikirku dalam hati.
Kini aku mulai menghargai apa yang telah disampaikannya itu. Ketulusan dalam menjalani perubahan, adalah sebuah kepastian yang paling baik. Satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian. Fisika modern mengekplorasi gagasan ini dalam teori Chaos, tapi itu tidak cukup berandai-andai tentang ketidakpastian. Karena kebahagiaan bukanlah bermain dengan konsep. Berbahagia adalah tahu bahwa kepastian itu hanya ilusi. Bukan sekedar tahu, tapi merasakannya secara langsung. Bahagia adalah penerimaan terhadap segala bentuk ketidakpastian.
Hal ini bukanlah kemurungan atau malapetaka. Tidak ada kesusahan dalam ketulusan akan perubahan. Jangan takut penerimaan ini sebagai menyebabkan kegilaan!
Nietzsche menjadi gila, justru karena kurangnya ketulusan. Seandainya dia tidak sibuk dalam konsep ketidakpastian, dia akan lebih waras dan bisa menikmati ketidakpastian ini.
Tidak ada cara lain.
“Tanpa kejernihan wawasan (insight), bagaimana mungkin kita menuntaskannya? Tak ada akhir dari itu. Kita takkan pernah menyelesaikan pembelajaran kita,” ujar Ajahn Chah, Sang Guru Tradisi Hutan.
Jangan takut!
Kita tidak perlu kekanak-kanakan. Jika memang ada yang berhasil menjebak saya, itu karena saya telah memberinya peluang untuk menjebak diriku. Pada akhirnya, akulah yang menjadi penyebab atas apa yang aku alami ini.
Banyak belajar adalah aksi yang didasari obsesi akan kepastian. Kepastian akan keberhasilan. Sejak kecil kita didoktrin untuk sekolah biar pintar, dan buntutnya selalu hidup sukses dan memiliki kekayaan berlimpah. Orang tua sering menasihatkan anak sulungnya untuk sukses lebih dulu, lalu ikut mengangkat harkat dan martabat adik-adiknya. Cita-cita yang tidak buruk, tapi sebenarnya bukan itu yang perlu menjadi tujuan kita.
Faust dikisahkan sebagai orang pintar yang gila ilmu, yang ingin belajar apa saja. Hingga suatu saat ingin lebih hebat lagi, dia menjual diri ke setan dan konon setan itu akan berjanji memberikan segala yang dimauinya.
Beberapa sastrawan mengartikan Faust sebagai simbol arogansi Barat, yang dirasa telah mencapai puncak peradaban. Kita tahu semua ilmu, ideologi, gaya hidup, bahkan lagu selalu berkiblat pada Barat. Jika tidak bisa mengikuti trend Barat, kita dianggap terbelakang dan ketinggalan zaman. Tapi aku mengartikan Faust sebagai diriku, sebagai diri kita semua, yang terobsesi mengejar segala kepastian dalam hidup.
Suatu saat aku terkejut. Bukankah Nietzsche, Sartre, Freud, mereka semua adalah orang pandai yang banyak ilmu, tapi mereka adalah orang yang menderita? Bukankah diriku juga, walaupun aku tidak sejenius mereka, tapi banyak buku yang kupelajari, aku jadi terluka oleh perasaan “sok tahu” yang membanggakan ini.
Benarkah banyak tahu itu otomatis tidak membuat kita bahagia? Apa tujuan hidup? Mungkin untuk lebih dekat dengan Tuhan. Atau mungkin untuk melayani Tuhan. Tapi sering aku jumpai mereka yang mengaku sebagai “pelayan Tuhan” justru tidak bisa melayani sesamanya dengan lebih baik. Mungkin dipikirnya orang lain bukanlah Tuhan, karena itu tidak dilayani sebaik Tuhannya.
Aku tidak suka dengan ide-ide Tuhan. Bukan berarti aku tidak berTuhan? Tapi karena Tuhan mudah sekali dipelintir demi hasrat pemenuhan pribadi, seperti opini pribadi, prinsip diri, termasuk identitas kelompok. Tuhan sebagai sosok yang agung, justru menjadi sosok yang paling mudah dikibuli manusia. Tuhan menjadi sebuah kemandekan, semacam kepastian yang dipaksa-paksakan.
Filsafat India yang menemukan angka nol, tidak menyukai kepastian mutlak. Bahkan Nagarjuna menyebutkan segalanya sebagai kosong, sunya. Kosong bukanlah atheis, tapi justru pemahaman akan realitas yang paling utuh dan sempurna. Kosong membuat kemandekan tidak memiliki ruang. Bahkan istilah “Tuhan” itu gak perlu lagi. Jika memang ada “Tuhan”, maka yang paling baik adalah tidak mendefinisikannya. Jika terpaksa, gunakan istilah yang berkonotasi bukan kemandekan. Entah itu Sunya, Tao, Tuhan Mistik, atau sekedar simbol. Theis tidaklah lebih bagus dibanding Atheis. Itu hanya istilah yang menjebak. Lebih penting menjadi spiritualis daripada Theis ataupun Atheis.
Spiritualitas adalah pengalaman yang diiringi penghayatan yang seutuhnya, saking utuhnya dia tak lagi berkata-kata. Berkomat-kamit adalah pertanda tidak tahu. Semakin banyak berbicara, dia semakin tidak bisa menjadi utuh. Robert Bernadette yang terinspirasi dengan Mistik Kristen menyebutkan hilangnya diri adalah memahami Tuhan. Selama ada diri yang berpikir, maka Tuhan itu tidak dapat diketahui. Konsekuensi, ketika Tuhan itu menjadi pengalaman, maka “tak terkata” adalah hasilnya.
Saya teringat sebuah kalimat bijak.
“Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan.” Itu ujar Sri Pannavaro Mahathera.
Aku tak mengerti arti ucapan itu pada waktu pertama kali mendengarnya.
“Ah, itu hanya permainan kata-kata,” demikian pikirku dalam hati.
Kini aku mulai menghargai apa yang telah disampaikannya itu. Ketulusan dalam menjalani perubahan, adalah sebuah kepastian yang paling baik. Satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian. Fisika modern mengekplorasi gagasan ini dalam teori Chaos, tapi itu tidak cukup berandai-andai tentang ketidakpastian. Karena kebahagiaan bukanlah bermain dengan konsep. Berbahagia adalah tahu bahwa kepastian itu hanya ilusi. Bukan sekedar tahu, tapi merasakannya secara langsung. Bahagia adalah penerimaan terhadap segala bentuk ketidakpastian.
Hal ini bukanlah kemurungan atau malapetaka. Tidak ada kesusahan dalam ketulusan akan perubahan. Jangan takut penerimaan ini sebagai menyebabkan kegilaan!
Nietzsche menjadi gila, justru karena kurangnya ketulusan. Seandainya dia tidak sibuk dalam konsep ketidakpastian, dia akan lebih waras dan bisa menikmati ketidakpastian ini.
Tidak ada cara lain.
“Tanpa kejernihan wawasan (insight), bagaimana mungkin kita menuntaskannya? Tak ada akhir dari itu. Kita takkan pernah menyelesaikan pembelajaran kita,” ujar Ajahn Chah, Sang Guru Tradisi Hutan.
Jangan takut!
Langganan:
Postingan (Atom)